KEMACETAN mengular ketika atas nama “rakyat” dan “demokrasi” sekelompok pengunjuk rasa memblokir jalan protokol.
Ada rasa masygul, juga bimbang.
Di satu sisi, rakyat diminta untuk bersimpati karena “nama”-nya dipinjam pada aksi mereka.
Pada sisi lain, entah berapa banyak lagi “rakyat” yang mengalami kerugian karena aksi itu, baik yang terlambat masuk kantor atau diomeli pelanggan gegara pesanannya telat diantar.
Sudah sebegitu tidak percaya dirinyakah para aktivis unjuk rasa di zaman sekarang?
Kalau memang isu yang mereka usung untuk berunjuk rasa itu betul-betul mewakili kepentingan rakyat, bukankah mereka tak harus bertindak seperti demikian hanya demi menarik perhatian?
Haruskah melakukan upaya “provokasi” semacam begitu, dengan opsi: "Gabung atau Macet?"
Demokrasi itu, pada hakikatnya, bukanlah sekadar adu banyak dan mengesampingkan akal sehat.
Ketidakpercayaan pada pemerintah ataulah pengamin kebijakan tentunya tak harus ditunjukkan dengan cara-cara yang menimbulkan ketidakpercayaan versi baru.
Pada relasi kapital, boleh jadi strategi tadi semacam pengejawantahan dari egoisme yang terlalu membuncah tanpa lagi memperhitungkan kepentingan alternatif.
Misalnya saja, demo buruh demi memperjuangkan upah, sudahkah mereka memperhitungkan juga nasib para pengganggur, atau kepentingan pihak-pihak yang masih mencari kerja?
Pertanyaannya, kalaulah tuntutan mereka dipenuhi, akankah itu berdampak langsung terhadap nasib para penganggur dan pencari kerja?
Yang pasti, dampak langsungnya hanya akan terasa oleh mereka yang kebetulan sudah menjadi buruh atau pekerja.
Sementara, bagi mereka yang masih menganggur, atau dalam proses pencarian, tentunya dampak itu bakal sangat delayed, atau bahkan takkan terasa sama sekali.
Catatan ini sekadar mengingatkan agar para aktivis tak terjebak pada pola pembentukan generasi “buta-tuli” yang baru, sebagaimana sudah berserakan di gedung-gedung pemerintah dan parlemen.
Jangan lagi membentuk karakter arogan dengan mengatasnamakan demokrasi dan rakyat, seperti yang sudah berjalan selama ini di gedung-gedung parlemen.
Kalau begitu jadinya kelak, hal itu tentu nyaris tak ada bedanya dengan ulah parpol yang selama ini selalu dituding hanya menjadikan demokrasi dan rakyat sebagai topeng dan atas nama belaka.
“Maaf, kenaikan harga BBM memang memberatkan. Tapi, kalau harus ditambah lagi dengan mendorong sepeda motor ke SPBU, gegara kehabisan di tengah kemacetan aksi unjuk rasa, ini sih sama saja dengan sudah jatuh tertimpa tangga,” kata sebuah ilustrasi yang tetiba melayang-layang di kepala.
Makna sebuah perjuangan bagi rakyat bakal terasa lebih sempurna bila tidak diiringi dengan hadirnya masalah baru.
Dalam benak saya, negara yang maju ataulah pemerintahan yang berhasil bukanlah yang memperbesar pemberian subsidi bagi rakyatnya, melainkan yang membuat seluruh rakyatnya mampu hidup berkecukupan tanpa subsidi sepeser pun.
Jadi, kata kuncinya adalah “pemberdayaan”, bukan “memperdaya”
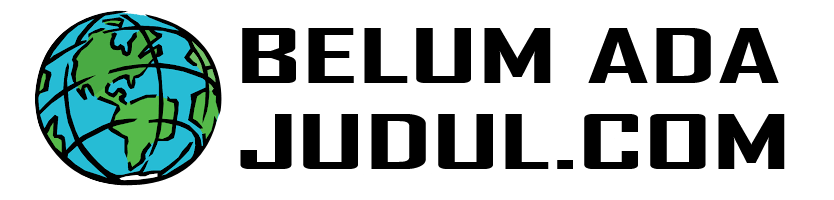

Post a Comment for "Topeng Demokrasi atas Nama Rakyat"